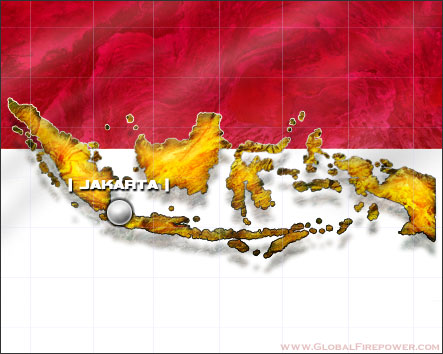Pertahanan (negara) adalah investasi. Negara yang kuat pertahanannya, aman, terjadi iklim yang damai.
– Prabowo Subianto –
Tanggal 25 November 2020 yang lalu, saya mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang mengambil tema “Sentralitas ASEAN Dalam Kontestasi Great Powers di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia”. FGD ini membahas hasil kajian yang dilakukan oleh Kemenkopolhukam RI bekerjasama dengan Parahyangan Center of International Studies (PACIS) Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
Kesempatan berharga itu saya manfaatkan untuk menyampaikan beberapa pandangan saya terkait diplomasi pertahanan Indonesia, yang karena kesibukan baru bisa saya muat dalam bentuk artikel kali ini.
BEBERAPA FAKTA[1]
1. Mengacu pada data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) April 2020, belanja militer di Asia Tenggara mengalami peningkatan 4,2% di tahun 2019 hingga mencapai 40,5 miliar Dollar AS, setelah sebelumnya mengalami penurunan 4,1% di tahun 2018. Bila dihitung dalam satu dekade 2010-2019, peningkatannya mencapai 34%.
2. Dari data di atas, tiga negara di kawasan ASEAN dengan belanja pertahanan terbesar di tahun 2019 adalah Singapura (28% dari total belanja pertahanan kawasan), Indonesia (19%), dan Thailand (18%). Beberapa negara di kawasan ASEAN meningkatkan belanja pertahanannya untuk memperkuat kemampuan angkatan perangnya sebagai reaksi atas klaim Tiongkok serta aktifitas mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS).
3. Masih dari data di atas, beberapa negara ASEAN dengan belanja pertahanan terbesar dalam hal persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 antara lain: Singapura 11.2 miliar Dollar AS (3.2% PDB), Indonesia 7.7 miliar Dollar AS (0.7% PDB), Thailand 7.3 miliar Dollar AS (1.3% PDB). Negara tetangga ASEAN, Australia mencatatkan belanja pertahanannya sebesar 25.9 miliar Dollar AS (1.9% PDB).

SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Perang pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk mempertahankan kepentingan nasional. Secara universal, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional semua bangsa adalah keberlangsungan hidup (sustainment of life) atau lebih sederhananya: bertahan hidup (survival). Mereka yang memiliki sedikit sumber daya untuk bertahan hidup akan merasa perlu memperjuangkan banyak hal bahkan hingga tingkat yang paling ekstrim yaitu dengan berperang. Namun, mereka yang memiliki banyak sumber daya untuk bertahan hidup, tidak boleh merasa tidak ada atau tidak banyak yang perlu mereka perjuangkan hingga harus berperang.
Semua perang yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia seperti ekspansi Kerajaan Romawi, Perang Salib, ekspansi Kerajaan Mongol, dua kali Perang Dunia, bahkan Perang Dingin yang tidak melibatkan konfrontasi fisik senjata antara dua negara adikuasa saat itupun, terjadi karena ada kelompok/negara yang ingin menguasai kelompok/negara lain, yang tentu saja untuk menguasai sumber dayanya bagi kepentingan hidup kelompok/negaranya. Fakta ini mengajarkan kepada kita bahwa memiliki sumber daya bukan berarti kita akan hidup dengan mudah, damai dan tenang. Semakin melimpah sumber daya yang dimiliki sebuah bangsa, justru menghadirkan tantangan yang makin besar untuk mempertahankan sumber daya itu bagi kemakmuran bangsanya dari kemungkinan dirampas, dijarah, dan dikuasai orang lain.
KONTESTASI GREAT POWERS
Kekuatan-kekuatan besar (Great Powers) secara umum didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan (dalam hal ini negara) yang dipandang memiliki kemampuan atau keahlian untuk menyebarkan atau menanamkan pengaruhnya pada tingkat global.[2] Saat ini, dunia pada umumnya menganggap negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Rusia, Inggris, juga Jerman dan Perancis adalah mereka yang termasuk dalam kategori Great Powers tersebut. Pengaruh yang disebarkan secara global ini bermacam-macam bentuknya: ekonomi (misalnya dalam wujud perdagangan dan perbankan), teknologi, sosial dan budaya, juga militer. Penggunaan mata uang Dollar AS sebagai standar mata uang dunia, meluasnya konsumsi makanan cepat saji, penggunaan platform-platform media sosial, merupakan bentuk-bentuk pengaruh yang berasal dari Great Powers tadi.
Dari perspektif militer, fenomena Great Powers sebenarnya merupakan evolusi dari bipolarisasi kekuatan di era pasca Perang Dunia II atau Perang Dingin, ketika AS dan Uni Soviet menjadi pusat kekuatan militer global. Setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, AS tampil sebagai satu-satunya orientasi kekuatan militer dunia. Meskipun masih dianggap sebagai pusat kekuatan militer dunia, hegemoni AS perlahan-lahan mulai “tergerus” sejak akhir era 1990-an, ketika Tiongkok tampil sebagai kekuatan ekonomi baru dan membangun militernya berbasis teknologi ciptaan mereka sendiri, serta Rusia yang mewarisi sebagian besar kapasitas industri pertahanan dari jaman Uni Soviet berusaha untuk membangun (kembali) pasar produk militernya. Meski demikian, geliat Tiongkok dan Rusia belum terlalu signifikan mempengaruhi peta kekuatan militer dunia, karena pasar kedua negara tersebut umumnya adalah negara-negara berkembang atau negara-negara dengan tata kelola yang buruk.
Di regional ASEAN, kontestasi Great Powers, setidaknya untuk saat ini, berpusat pada persaingan AS dan Tiongkok, terutama di kawasan ekonomi Laut Tiongkok Selatan (LTS). Hal ini karena secara geografis, beberapa negara ASEAN secara langsung terdampak oleh kebijakan-kebijakan sepihak Pemerintah Tiongkok atas klaim mereka di LTS, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan tentu saja Indonesia. Persoalannya, seberapa mampu ASEAN sebagai sebuah entitas multilateral meminimalisir dampak manuver-manuver masif Tiongkok di kawasan tersebut?
Kembali pada filosofi dasar “sustainment of life” atau “survival” tadi, LTS menjadi menarik karena kawasan tersebut adalah kawasan dengan nilai strategis dan ekonomi tinggi yang dapat membantu siapapun “bertahan hidup”. Namun, LTS juga merupakan “jembatan”, baik secara fisik/geografis maupun politis/diplomatis bagi perluasan kepentingan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, yang tentu saja sangat mengganggu AS. Sejarah mencatat, kawasan Asia Tenggara adalah salah satu “area of interest” AS sejak lama, bila kita melihat pada masa Perang Dunia II, pemberontakan-pemberontakan di Indonesia pasca kemerdekaan hingga 1960-an sampai penggulingan Soekarno tahun 1966, Perang Vietnam, akuisisi Timor Timur oleh Indonesia, dan masih banyak lagi. AS membangun pangkalan militer di Filipina sejak 1947 hingga 1992, dan masih memiliki akses untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Filipina, dan tentu saja sekutu dekat mereka Australia.
PERAN ASEAN

Association of South East Asia Nations (ASEAN), sejak dibentuk tahun 1967 telah memainkan peran sentral sebagai sebuah komunitas menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan ini. Keanggotaan yang awalnya terdiri atas lima negara pendiri, saat ini telah berkembang menjadi dua kali lipatnya setelah lima negara berikutnya bergabung dalam periode antara 1984 hingga 1998. Fokus kerja sama ASEAN adalah di sektor ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan informasi. Meskipun berdiri di atas prinsip-prinsip perdamaian, kesetaraan, dan saling menghormati, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sejarah masing-masing negara anggotanya berpeluang memunculkan gesekan-gesekan khususnya di sektor pertahanan.
Heterogenitas negara-negara ASEAN menghadirkan sebuah tantangan tersendiri dalam menyatukan visi di bidang pertahanan dan keamanan kawasan. Keterikatan historis negara-negara anggotanya dengan beberapa negara besar di luar kawasan telah menghasilkan orientasi pembangunan pertahanan yang beragam di antara sesama anggota ASEAN. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam misalnya, mereka adalah bagian dari The Commonwealth yang dipimpin oleh Inggris. Filipina, meskipun di bawah Presiden Rodrigo Duterte terlihat agak “menjaga jarak” dengan AS, namun pada faktanya sangat bergantung pada Pemerintah AS dalam memperkuat militernya—sekali lagi karena faktor historis. Vietnam, terlepas dari konflik akhir-akhir ini dengan Tiongkok di LTS, membangun reformasi sosialisme mereka dengan belajar dari Tiongkok, lagi-lagi karena faktor historis.
Faktor historis membuat beberapa negara ASEAN memiliki apa yang disebut sebagai “floating multilateralism” atau multilaterisme mengambang yang memungkinkan beberapa negara ASEAN membangun koneksitas yang demi kepentingan pragmatis bisa saja melebihi koneksitas mereka dengan ASEAN itu sendiri. Multilateralisme mengambang, bila dibawa ke ranah militer atau pertahanan negara, seperti koneksitas Five Power Defence Arrangement (FPDA) antara Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru dan Inggris, tentu menjadi sebuah tantangan dan ujian besar bagi “ASEAN Bersatu”. Ujian ini pernah dialami ASEAN dalam sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang berujung pada lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI tahun 2002.
Dalam KTT ASEAN di Bangkok bulan Juni 2019, para pemimpin negara-negara ASEAN mengadopsi sebuah konsep politik regional yang bertajuk “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”. Pandangan ASEAN ini berdasarkan pada prinsip-prinsip memperkuat sentralitas, keterbukaan, transparansi, inklusifitas ASEAN, kerangka kerja berbasis peraturan, good governance, penghormatan atas kedaulatan, non-intervensi, ketaatan terhadap kerangka kerjasama yang sudah ada, kesamaan, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap hukum internasional seperti UN Charter, UNCLOS 1982 dan peraturan-peraturan internasional lainnya, serta ASEAN Charter dan berbagai kesepakatan regional lainnya.[3]
Secara subyektif, saya melihat ASEAN Outlook ini sebagai sebuah paradoks: di satu sisi ASEAN Outlook on Indo Pacific berfokus kepada area kerjasama non-militer (Maritime Cooperation, Connectivity, UN Sustainable Development Goals 2030, Economic and other areas), namun di saat yang sama, kontestasi Great Powers mengindikasikan eskalasi di sektor militer yang akan berdampak pada stabilitas kawasan. Sengketa LTS adalah contoh di mana konflik militer di kawasan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, meskipun itu bukan antar negara ASEAN. Namun sejarah mencatat bahwa hubungan militer di antara negara-negara anggota ASEAN layaknya “api dalam sekam”: dingin di permukaan, namun “panas” di dalam (contohnya sengketa wilayah Ambalat).
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA
Kecenderungan eskalasi ketegangan di kawasan LTS tentu harus disikapi serius oleh ASEAN, tidak hanya untuk stabilitas kawasan, namun juga tak kalah pentingnya adalah untuk menjamin agar ASEAN sendiri tidak “terpecah”, karena meskipun secara kuantitatif musuh yang dihadapi sama (Tiongkok), namun secara kualitatif kepentingan tiap negara ASEAN yang terkait dengan LTS bisa saja berbeda. Perbedaan kepentingan ini sangat berpeluang memunculkan orientasi pragmatis dalam pengembangan kekuatan militer tiap-tiap negara, dengan mengatasnamakan sengketa LTS.
Meskipun terkesan normatif dan sedikit naif, namun diplomasi pertahanan tetap menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan demi tetap terjaganya stabilitas kawasan ASEAN. ASEAN memiliki forum-forum seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM Plus yang melibatkan para Menteri Pertahanan dari delapan negara mitra ASEAN (AS, Tiongkok, Rusia, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru). Namun demikian, fakta masih terjadinya beberapa sengketa perbatasan, termasuk pelanggaran wilayah baik di darat, laut maupun udara di antara sesama anggota ASEAN menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan bukan sebuah solusi tunggal.
Setidaknya, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam hal diplomasi pertahanan ini, baik secara umum maupun khusus dalam konteks kontestasi Great Powers:
1. Pada suatu titik ketika dampak kontestasi Great Powers sudah dipandang membahayakan kepentingan negara ASEAN tertentu, sebuah negara bisa mengambil langkah pragmatis. Dalam kasus Filipina versus Tiongkok di Arbitrase LTS 2016 (The Hague) yang hasilnya diabaikan sama sekali oleh Tiongkok (meskipun mereka termasuk dalam UNCLOS 1982) misalnya, Filipina tentu merasa mereka tidak dapat mengandalkan ASEAN, dan bisa jadi lebih memilih untuk memanfaatkan floating multilateralism mereka dengan AS (yang tentu saja akan dimanfaatkan AS dengan senang hati).
2. Diplomasi pertahanan, yang bertujuan mewujudkan perdamaian kawasan tetap harus didukung dengan “kesiapan berperang”. Si vis pacem, para bellum. Diplomasi pertahanan Indonesia jangan sampai menimbulkan interpretasi bahwa itu adalah upaya Indonesia karena tidak siap berperang. Fakta bahwa beberapa pelanggaran wilayah oleh kekuatan militer negara tetangga masih terjadi hingga saat ini (yang terlalu naif untuk dikatakan “tidak sengaja”) menunjukkan bahwa Indonesia masih belum terlalu “dianggap”, bahkan di tingkat kawasan.
Mendiang Presiden AS John Fitzgerald Kennedy pernah berkata “It is an unfortunate fact that we can secure peace only by preparing for war”. Itu berarti bahwa diplomasi pertahanan untuk tujuan stabilitas dan perdamaian (kawasan) juga harus diikuti dengan pembangunan kekuatan pertahanan, atau kesiapan untuk berperang. Diplomasi pertahanan dan pembangunan kekuatan pertahanan layaknya dua sisi mata uang yang memberi keuntungan timbal balik: diplomasi pertahanan dapat meningkatkan kesiapan berperang; kesiapan berperang akan memperkuat posisi diplomasi pertahanan.
Diplomasi pertahanan harus dilihat sebagai suatu upaya atau tindakan yang sistematis, dan melibatkan semua elemen nasional. Diplomasi pertahanan haruslah berupa pendekatan “kesisteman Indonesia”. Belajar dari para Great Powers, kuatnya posisi diplomasi pertahanan mereka banyak ditentukan oleh kuatnya ekonomi, majunya industri (tidak hanya industri sektor pertahanan), kuatnya political will pemerintah, tingginya tingkat literasi atau keterdidikan masyarakat, mapannya tata kelola negara, dan faktor-faktor lainnya.
Di sisi lain, pembangunan kekuatan pertahanan agar “siap berperang” juga harus dilihat dengan pendekatan yang sama: “kesisteman Indonesia”. Semua elemen harus terlibat, tidak hanya Kementerian Pertahanan atau TNI. Pembangunan kekuatan pertahanan bukan semata-mata soal defence spending atau belanja pertahanan. Membangun pertahanan untuk sebuah negara seluas Indonesia dengan mengandalkan defence spending, selain memerlukan biaya besar, juga tidak menjamin adanya daya gentar dalam jangka panjang. Kita dapat melihat besarnya defence spending di beberapa negara kaya di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab atau Qatar, yang secara kualitatif tidak menghasilkan rasa takut atau segan negara-negara lainnya.
Diplomasi pertahanan Indonesia akan lebih kuat, berpengaruh, diperhitungkan dan dihormati di kawasan bila Indonesia secara serius menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten untuk membangun pertahanan negara yang tangguh, dengan mengubah paradigma dari defence spending ke defence investment. Defence investment adalah pembangunan dan pengembangan segenap sumber daya pertahanan: Alutsista, sumber daya manusia (SDM), research and development (R&D), industri pertahanan, serta tata kelola pertahanan negara berupa struktur, doktrin, strategi hingga taktik. Bila ini dijalankan, dalam jangka panjang belanja pertahanan akan menjadi asset, bukan hanya beban atau liability. Negara-negara seperti Iran dan India memiliki posisi diplomasi pertahanan yang bagus tidak hanya di kawasan mereka, namun juga di tingkat global, bukan semata-mata dengan defence spending, namun juga dengan kemandirian industri mereka dan kekuatan political will pemerintahnya.
Itulah tantangan pembangunan kekuatan diplomasi pertahanan kita, agar kita lebih disegani dan dihormati, setidaknya di kawasan ASEAN, di tengah perjuangannya menghadapi dampak kontestasi Great Powers. Siapapun yang ingin hidup damai, tenang dan nyaman, harus siap untuk berperang.
Si
vis pacem, para bellum.
[1] https://www.sipri.org/databases/milex, diunduh tanggal 21 November 2020
[2] https://www.webcitation.org/5kwqEr8pe, diunduh 30 Januari 2021
[3] https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, diterjemahkan tanggal 24 November 2020.