Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF Suzuki 2012 setelah dikalahkan Malaysia 0-2 tentu mengecewakan kita semua. Negeri ini telah terlalu haus untuk merasakan kembali prestasi di cabang sepakbola-cabang olahraga yang diklaim memiliki penggemar terbanyak. Kita maklum, dengan penduduk yang berkisar 270 juta-an jiwa, negara seperti kesulitan mencari 11-20 orang yang punya kualitas bermain bola. Parahnya, itu terjadi setelah konflik internal di tubuh pengelola sepakbola Indonesia yang berlarut-larut. Organisasi resmi bernama PSSI yang telah berdiri puluhan tahun tidak berdaya saat digerogoti oleh internalnya sendiri. Lalu muncul sekelompok orang yang mengaku dirinya “pencinta” sepakbola Indonesia, tapi ujung-ujungnya juga hanya memperkeruh situasi. Hasilnya bisa kita lihat, tak hanya sepi tropi & prestasi di ajang-ajang seperti SEA Games, Asian Games (alih-alih Olimpiade) maupun Piala Asia (alih-alih Piala Dunia), kita bahkan sama sekali “tak masuk hitungan” di regional Asia Tenggara-yang beberapa puluh tahun lalu kita kuasai.
Pagi ini saya membaca sebuah artikel di sebuah media informasi berbasis internet, bahwa seorang mantan juara dunia perahu naga asal Jambi sedang mengalami kesulitan membiayai perawatan anaknya (yang belum genap 2 tahun) yang menderita pengerapuhan kulit. Deretan medali, piagam, sertifikat serta berbagai penghargaan nasional & internasional yang dimilikinya ternyata hanya membawanya pada kehidupan saat ini sebagai seorang buruh cuci. Dengan itu, plus penghasilan suaminya yang hanya sekitar 1 juta rupiah per bulan sebagai seorang cleaning service di DPRD Jambi, tentu sulit untuk membiayai pengobatan anaknya yang memerlukan biaya sekitar 1,5 juta rupiah sebulan di RSCM.
Ironis. Ya, saat negara membutuhkan peran, tenaga, pikiran & keterampilan atlet-atet kita untuk mengibarkan Sang Merah Putih serta mengumandangkan Indonesia Raya, negara justru abai & membiarkan para duta ini mendapat malu, & bergumul sendiri dengan kesulitan hidupnya. Negara dengan kekuasaannya yang semestinya bisa berbuat sangat banyak untuk menyelesaikan konflik di sebuah institusi resmi, serta berlimpah anggaran dalam membangun prestasi, justru sibuk berdalih.
Kisruh PSSI vs KPSI sebenarnya bisa dituntaskan bila negara sunguh-sungguh & berkomitmen terhadap pembangunan prestasi sepakbola. Kisah yang dialami Leni, sang juara dunia dayung itu, juga tak perlu terjadi seandainya negara sadar bahwa di sisi lain, sekian miliar rupiah justru dinikmati oleh para pengelola olahraga negeri ini melalui berbagai proyek seperti Wisma Atlet atau Hambalang.
Olahraga hanyalah salah satu dimensi hidup di negeri ini yang dapat membuat rakyat dapat melupakan berbagai kekacauan serta ketidakbecusan pengelola negara yang berdampak pada berbagai masalah bangsa. Olahraga-lah yang membuat rakyat kecil masih punya kebanggaan ber-Indonesia, masih mencintai Merah Putih, serta tidak malu untuk berkata “Saya orang Indonesia!”.
Kita tak perlu naif dengan fakta bahwa seperti apapun kemajuan ekonomi (makro) yang digembar-gemborkan pemerintah itu, masih banyak hal yang dapat menjadi indikator ketertinggalan kita dari berbagai negara yang dulu justru belajar dari kita. Mari kita bicara yang gampang-gampang saja: beranikah kita menyandingkan kelas Ibukota Negara Jakarta dengan ibukota tetangga kita seperti Singapura atau Kuala Lumpur?; beranikah kita membanggakan produk nasional kita seperti Malaysia bangga dengan Proton-nya?; beranikah kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat di pulau terluar atau perbatasan saat kita harus membandingkannya dengan apa yang dilakukan Malaysia terhadap perkampungan mereka di perbatasan yang sama?
Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai negeri ini, saya khawatir bahwa pengelola negara ini sudah terjebak dalam pragmatisme kuantitas. Semua diukur dengan angka, persentase, rupiah/dollar, dsb. Kita terlalu ignorant pada kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang kita sebut positif itu adalah angka dalam persen; tidak lebih. Tapi fakta bahwa kita masih mengimpor bahan pangan, bahkan di beberapa daerah masyarakatnya masih mengalami malnutrisi & kekurangan pangan (saat sejak kecil kita diajari bahwa Indonesia negara agraris) adalah soal kualitas: kualitas manajemen pangan yang buruk, apakah itu di bidang penelitian, pembudidayaan benih, pengelolaan lahan, distribusi, hingga pengendalian harga. Tak perlu berdalih & menutup mata, karena itu semua ada di negeri ini.
Memang, di sisi lain kita juga patut berharap bahwa ada segelintir orang yang ketokohannya dapat mencuatkan harapan kita akan sesuatu yang lebih baik. Namun ini juga bukan pembenaran bahwa negara bisa abai terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa sedikit orang-orang baik ini akan berhadapan dengan tembok & badai “pro status quo” yang telah sangat sistematis & terorganisir, yang dimotori oleh sekelompok orang yang tak rela zona nyamannya di-“utak-atik”.
Saya percaya, bahwa pada saat John F. Kennedy mengatakan dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden AS tahun 1961 “Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country“, ia tak pernah sedikitpun bermaksud bahwa negara bisa berbuat atau abai semaunya terhadap warganya…

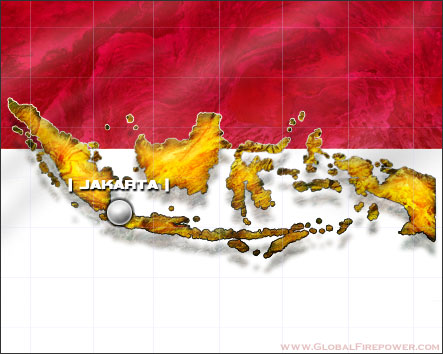
Memang ironis bang,
Alih isu dengan kebencian terhadap tetangga justru di gadang2kan, padahal mereka menang, mereka lebih maju itu target pencapaian mereka yg ingin maju. Namun, kita hanya jalan ditempat menyalahkan orang lain utk menutupi kebodohan dan kegagalan kita sendiri.
Salam
Betul Ted. Buruk muka cermin dibelah… 🙁
Hitungan dalam persen bang,
Misal : ternyata hanya 10% org miskin di Indonesia, dan 10% itu adalah 24.000.000 nyawa..suatu jumlah yg “fantastis”
Exactly Ted 🙁
Disini Mas,.. bernama Indonesia dengan sebutan Tanah Surga…. Katanya 😀
Sebuah ironi yang sedikit banyak mengilhami anak muda sekarang untuk APATIS dalam membela nama bangsanya….
Hehehe…betul Mas. Ini ironi negeri yg katanya “Zamrud Khatulistiwa”, “Kolam Susu” dsb…