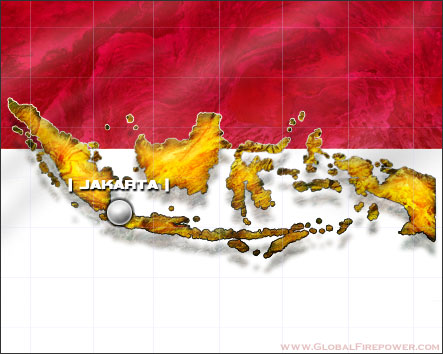Tahun 2013, untuk ke-68 kalinya negeri ini merayakan dan memperingati momen terpenting dalam perjalanan sejarahnya: Proklamasi 17 Agustus 1945. Kita menyebutnya “Proklamasi Kemerdekaan”. Ya, karena dalam teks Proklamasi yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu disebutkan “….menyatakan kemerdekaan Indonesia….”. Dalam konteks kala itu, memang tepat apa yang dinyatakan para pendiri bangsa ini. Saat itu kita memang terjajah secara fisik, dan hak-hak manusia Indonesia terampas oleh kekuasaan penjajah.
Kata “merdeka” secara harfiah berarti “bebas”. Kata ini diambil dari bahasa Sansekerta “maharddhika” yang berarti “kaya, sejahtera, dan kuat”. Dalam konteks situasi dan kondisi Indonesia saat itu, kebebasan memang tidak ada, kekayaan dan kesejahteraan hanya milik mereka yang bersedia menjual diri dan bangsanya kepada penjajah, sedangkan kekuatan adalah milik penjajah. Dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, terjadi kevakuman aktifitas Jepang di Indonesia, dan momentum ini dimanfaatkan oleh Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Nah, dalam konteks sekarang, dengan kondisi Indonesia dan dunia yang sudah banyak berbeda dengan tahun 1945, apakah kata “merdeka” itu tepat? Dengan kata lain, apakah saat ini kita—bangsa Indonesia—benar-benar sudah merdeka? Mari kita urai beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk dapat melihat apakah kita memang merdeka. Secara ideologi, pandangan hidup bangsa yang bernama Pancasila memang sudah terbukti kokoh di tengah berbagai upaya untuk menjatuhkannya. Namun kita juga tidak boleh naif, bahwa saat ini ideologi luhur ini masih sangat rawan terhadap ancaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya teknologi informasi/TI) telah menyebarkan virus liberalisme akut. [Ingat bahwa seorang tokoh nasional bahkan pernah menyodorkan wacana “Negara Federasi Indonesia” seperti Amerika Serikat]. Pancasila—yang memberi hak serta ruang yang sama bagi keyakinan apapun di bumi Indonesia sesuai sila pertamanya—juga tengah dirongrong oleh upaya-upaya untuk mendiskrimasikan keyakinan tertentu yang dilindungi serta disahkan oleh Undang-Undang.
Secara politik, bangsa ini belum bisa membebaskan dirinya dari ancaman tergerusnya keseimbangan di antara elemen-elemen politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita mengklaim diri sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensiil, namun faktanya lembaga legislatif justru lebih (ingin) menunjukkan dominasinya dalam pengambilan kebijakan nasional. Lembaga yudikatif tidak asing dengan intervensi eksekutif, dan legislatif kita—yang notabene adalah “wakil rakyat”—tidak menunjukkan kejelasan mewakili rakyat yang mana.
Secara ekonomi, kemerdekaan bahkan tampak masih jauh. Apa yang didapat bangsa ini dari kekayaan alamnya yang konon berlimpah ruah itu? Tanah yang subur ternyata tidak mampu menghindarkan negeri ini dari impor beras, gandum, dan sebagainya. Alih-alih memberi kekayaan bagi negara, tambang emas dan tembaga di Papua bahkan tidak mampu menyejahterakan masyarakat Papua sendiri. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kekayaan laut yang berlimpah juga tidak mampu membebaskan para nelayan dari kemiskinan. Belum lagi penjajahan korporasi multi-nasional (Multinational Corporation atau MNC) yang membuat rupiah Indonesia mengalir deras ke negara-negara lain melalui restoran-restoran cepat saji, wholesale, dealer-dealer otomotif, serta waralaba-waralaba yang berbasis di luar Indonesia (yang sukses menindas pasar tradisional yang sejatinya dapat menjadi salah satu perekat komunitas).
Secara sosial, dunia pendidikan kita ditindas dengan sekularisme, sehingga anak-anak menjadi “dewasa” sebelum waktunya. Nilai-nilai keindonesiaan nyaris lenyap di sekolah-sekolah, yang menggilas patriotisme dan nasionalise generasi muda. Dalam aspek budaya, masyarakat Indonesia telah terjajah oleh kultur asing dalam wujud film-film Hollywood dan karya seni asing lainnya ketimbang memberikan ruang serta membangun karya anak bangsa sendiri. Orang lebih suka mengejar impian ke ibukota negara ketimbang membangun kampung halamannya sendiri, karena mereka ingin menjadi pria-pria berjas dan berdasi, serta wanita-wanita dengan penampilan cantik dan “smart” ala selebriti atau wanita karier. Hedonisme telah mengangkangi pola pikir masyakarat yang mengukur kesuksesan mereka dengan frekwensi berbelanja di mall, makan di restoran asing, menghabiskan waktu di kafe dan klub malam, atau banyaknya mobil yang ada di garasi serta banyaknya gadget yang menjadi pegangan anggota keluarga. Individualisme dan egoisme merebak di mana-mana, sehingga tidak heran bila korupsi terjadi di semua lini, segala strata, dan masif. Apapun caranya adalah halal, yang haram adalah menjadi miskin dan tidak punya apa-apa.
Di bidang pertahanan, bangsa ini “menikmati” dirinya dijadikan tempat sampah untuk barang-barang bekas orang lain. Hebatnya lagi, sudah dijadikan tempat pembuangan, kita harus membayar pula dalam jumlah yang tidak kecil. Kita bahkan tidak berdaulat terhadap ruang udara kita sendiri, dan memasrahkan pengendalian ruang udara di sebagian wilayahnya kepada negara yang besarnya hanya se-“jempol kaki”. Kitapun tetap happy menjual pasir kepada negara kecil itu yang membuat wilayah teritorialnya makin luas, dan batas laut kita makin menyusut. Kita hanya bisa “melongo” ketika puluhan penerbangan gelap melintasi wilayah udara kita setiap tahunnya. Bangsa ini juga tak berkutik ketika ia diwajibkan untuk terus membeli dan bergantung pada produk asing, dan tak berdaya ketika orang lain tak “mengijinkannya” mengembangkan industrinya sendiri.
Itu baru dalam perspektif kita dengan “kekuatan” asing. Di kalangan sesama anak bangsa, penjajahan itu juga terjadi. Ribuan orang harus kehilangan “kehidupan”-nya di Porong, Sidoarjo akibat ulah salah satu perusahaan—yang diindikasikan—pengemplang pajak yang menenggelamkan rumah-rumah mereka dalam lumpur. Hebatnya, salah satu bos perusahaan itu tenang-tenang saja menikmati jabatannya di pemerintahan saat ribuan rakyat menderita. Di beberapa daerah, sebagian penganut agama/keyakinan tertentu masih harus berjuang keras untuk mendapatkan kebebasan menjalankan keyakinannya (misalnya memperoleh ijin mendirikan rumah ibadah). Di beberapa kota besar seperti Jakarta, pedagang harus membayar “upeti” kepada para preman, baik preman bertampang kasar maupun mereka yang berbalut seragam aparat. Masyarakat juga masih asing dengan pengurusan berbagai dokumen administratif (KTP, SIM, IMB, dsb) yang bebas pungutan liar. Pagar makan tanaman, bapak mencaplok anaknya sendiri, dan kakak menindas adiknya—seperti itulah gambarannya.
Semua yang saya sebutkan di atas hanya sebagian contoh. Garis besarnya: kita sama sekali belum bisa membebaskan diri dari ancaman, tekanan, dan pengaruh asing dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama dengan ketidakmampuan kita membebaskan diri dari tekanan penjajah sebelum tahun 1945. Lantas, kapan kita merdeka? Nanti, ketika bangsa ini (terutama para pemimpinnya) bisa membebaskan alam pikirnya dari penjajahan para dajjal, lucifer atau apapun namanya. Saat kita benar-benar merdeka, uang tak lagi berada di atas akhlak, kekuasaan tak lagi menginjak-injak hukum, dan modernisasi tak lagi mengabaikan nilai-nilai moral.
“Maharddhika” alias “kaya, sejahtera, dan kuat” itu masih jauh. Enam puluh delapan tahun sejak 17 Agustus 1945, bangsa ini baru sekedar (belajar) bernegara, BUKAN merdeka…